Anak Muda dan Kekerasan Beragama: Dua Pilihan Jalan
Contents
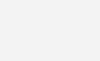
Puluhan tahun lalu, Soekarno meminta sepuluh orang pemuda untuk mengguncangkan dunia. Ini secara tidak langsung memberikan gambaran kepada kita betapa penting posisi anak muda. Kita kerap menganggap mereka sebagai harapan hari mendatang, sosok yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Bagi saya, anak muda memang bukan segala-galanya, tapi hampir sampai di titik segalanya tersebut.
Posisi Anak Muda dan Kekerasan Beragama
Dalam konteks kekerasan beragama, misalnya, para pemuda berada di posisi yang tidak mudah. Pertama, kita berharap bahwa mereka menjadi eksponen orang yang menyuarakan kebebasan beragam dan sejenisnya. Sayangnya, di saat yang sama, mereka juga tidak mempunyai posisi yang jelas akan hal tersebut. Ada banyak studi yang menjelaskan bahwa masa-masa tersebut merupakan fase pencarian jati diri.
Sebabnya, harapan bahwa anak muda menjadi pelopor dalam kebebasan beragama masih berada taraf harapan. Lantas, bagaimana secara praktis? Dalam realita yang kita temui, tidak sedikit dari mereka yang malah menjadi kontra dengan kebebasan beragama. Anak muda yang eksklusif atas nama agama lalu enggan untuk bergaul dengan orang yang berbeda pandangan keagamaan.
Pencarian Jati Diri
Masa tersebut merupakan fase, di mana seseorang mencari jati dirinya. Kurang mujurnya adalah pada fase ini mereka harus bertemu dengan media sosial. Padahal, kita tahu bahwa konten-konten keberagamaan yang inklusif masih berada dalam taraf minim. Dengan bahasa lain, masa pencarian jati diri ini akan bertemu dengan konten di media sosial yang cenderung tidak inklusif.
Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan barangkali hanya dengan memperbanyak konten. Ini adalah satu-satunya cara untuk membangun kesadaran anak muda. Kita harus memahami bahwa golongan-golongan yang cenderung eksklusif beragama menjadikan anak muda sebagai sasaran mereka. Artinya, baik kelompok yang toleran dan intoleran sama-sama mengejar anak muda. Inilah yang saya sebut dua pilihan jalan.
Sebuah Sikap Pesimis
Kendati demikian, saya sedikit pesimis soal anak muda ini. Memang benar bahwa mereka mulai mempunyai kesadaran akan kebebasan dan keberagamaan nirkekerasan. Namun, itu bukan berarti tidak ada sama sekali anak muda yang masih terperangkap dalam nalar keras. Anak-anak ini di Sekolah Menengah Atas, sebagaimana dalam beberapa riset, masih mempunyai sikap khawatir terhadap golongan yang berbeda agama.
Ini adalah angin buruk, sebab di benak mereka sudah tertanam benih-benih eksklusivisme. Benih itulah yang suatu saat nanti bakal menjadi pohon—bahkan berbuah—intoleransi beragama. Kiranya, kurikulum yang memadai dan mengakomodir keberagamaan yang inklusif menjadi sangat penting. Sudah waktunya sekolah menanampan pendidikan yang memberikan pemahaman terhadap keberagaman dan pluralitas.
Sekali lagi, saya akui bahwa anak muda memang harapan kita untuk mengampanyekan keberagamaan tanpa kekerasan. Namun, jangan lupakan bahwa mereka sedang bingung berada di antara dua pilihan jalan. Apakah mereka hendak menyuarakan agama tanpa kekerasan atau malah masuk ke sirkel orang yang keras dalam beragama? Wallahu A’lam.





Tinggalkan Balasan