Merangkai Toleransi Melalui Histori, Interpretasi dan Teologi
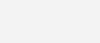
Membincang toleransi kaitannya dengan komunitas beragama, ada satu teori favorit saya. Teori ini dikembangkan oleh Alan Race, salah seorang teolog Gereja Anglikan. Race sendiri merupakan murid dari John Hick, tokoh kunci dalam diskursus pluralisme agama. Terlepas bahwa teori tersebut di kemudian hari dikuliti oleh Gavin D’Costa, bagi saya tetap penting untuk diajukan. Teori tersebut adalah tipologi tripolar (threefold typology).
Dalam pandangan Race, terdapat tiga tipologi pandangan seseorang terkait komunitas religius di luar dirinya. Mulai dari eksklusivisme, inklusivisme, hingga pluralisme. Terminologi pertama, secara sederhana biasa diartikan sebagai pandangan yang mendudukkan agama sendiri yang paling benar, agama lain salah.
Kontra dengan itu, yakni tipologi inklusivisme. Para inklusivis adalah orang-orang yang menganggap bahwa setiap agama dan keyakinan mempunyai kebenarannya masing-masing. Hanya saja, hal tersebut masih menganggap agama sendiri sempurna. Puncak dari tipologi tersebut adalah pluralisme yang menegasikan superioritas agama yang satu di atas agama lainnya. Setiap agama, menurut pandangan ini, akan sampai kepada kebenarannya sendiri-sendiri.
Dua Sumber Masalah
Dari klasifikasi tersebut, hemat saya, hanya dua tipologi terakhir yang ideal. Sementara tipologi pertama (baca: eksklusivisme) merupakan pandangan yang bisa meretakkan koeksistensi. Sayangnya, pandangan eksklusif dalam beragama masih berada di poros utama. Pertanyaannya, dari mana pandangan-pandangan tersebut berasal? Saya hendak mengetengahkan dua jawaban. Pertama, dari pemahaman sejarah yang tidak komprehensif. Kedua, diakui atau tidak hal tersebut termotivasi dari kitab suci.
Sebagian besar umat muslim menganggap bahwa relasi Islam dan nonislam pada fase awal senantiasa berkonflik dan konfrontatif, padahal tidak demikian. Hubungan antara Islam dan nonislam pada fase awal bisa dibilang sangat fluktuatif. Benar bahwa terdapat konflik, namun hal tersebut tidak bisa menafikan hubungan yang baik antara Islam dan nonislam di sisi lain. Inilah mozaik sejarah Islam awal yang kerap dilupakan. Akibatnya, sebagian besar muslim mengira bahwa pertengkaran Islam dengan komunitas religius lain sudah berakar sejak fase awal.
Dengan melakukan penelurusan sejarah yang komprehensif, kita akan mengetahui bahwa nabi mempunyai hubungan baik dengan penganut agama yang berbeda. Bahkan, beberapa orang Yahudi disebutkan membantu nabi di dalam sebuah peperangan. Pandangan-pandangan semacam ini jarang—untuk tidak mengatakan tak ada—dalam pengamatan mainstream umat Islam.
Hal kedua yang menjadikan seseorang eksklusif adalah motivasi dari kitab suci. Tidak hanya eksklusivisme, bahkan Al-Qur’an bisa saja dijadikan pijakan untuk melakukan teror dan tindakan kekerasan atas nama agama. Maka, hal terpenting yang harus diletakkan pertama adalah keterbukaan kitab suci untuk ditafsirkan kembali.
Pada hakikatnya, pembacaan yang eksklusif terhadap kitab suci tersebut hanya salah satu penafsiran. Dengan kata lain, penafsiran tersebut bisa dikoreksi dan direvisi. Sudah banyak sarjana muslim belakangan yang mencoba untuk melakukan penafsiran kembali. Hal ini samata-mata agar kitab suci suportif untuk keberlangsungan koeksistensi antar umat beragama.
Melalui dua langkah yang saya ajukan di atas, kemungkinan keterbukaan untuk menerima kelompok agama yang berbeda semakin menemukan jalan terangnya. Sejatinya, ada salah satu langkah lagi yang saya sadur dari salah seorang intelektual muslim Turki, Mustafa Akyol, dalam buku-nya, Reopening Muslim Minds. Akyol mengajukan tawaran toleransi dengan berbasis kepada teologi, secara spesifik teologi irja’ (ingat golongan Murji’ah!).
Teologi Penangguhan
Terkait irja’ ini kita dapat menariknya pada perseteruan antara Muawiyah dan Ali. Dua sekte besar lahir akibat proses arbitrase (tahkim) yang dilakukan keduanya. Orang-orang yang setia pada Ali (disebut Syiah) dan orang yang mengutuk Ali. Di tengah kecamuk ini, gagasan irja’ mengemuka dan pengikutnya disebut sebagai Murji’ah. Secara terminologi irja’ dapat dimaknai sebagai penundaan, secara spesisifik orang yang memberikan penundaan vonis untuk Ali dan Muawiyah.
Secara gamblang dapat dikatakan bahwa vonis hanya diberikan kelak di hari penghakiman. Satu-satu zat yang dapat memberikan vonis, mana yang salah dan mana yang benar, hanyalah Tuhan. Vonis diletakkan semata-mata sebagai hak prerogatif-Nya. Di sinilah teologi irja’ ini menemukan signifikansinya sebagai kredo agar kita menunda untuk memberikan penghakiman terhadap kelompok yang berbeda.
Untuk memperkuat ini, Akyol menyinggung drama Nathan the Wise. Sebuah drama dari sastrawan Jerman, Gotthold Ephraim Lessing (m. 1781) yang menggambarkan tiga (jumlah ini tentu bisa bertambah) cincin. Tiga agama Abrahamik, misalnya, diibaratkan sebagai tiga cincin yang sama berharganya.
Dari ketiganya hanya satu yang benar-benar asli, namun orang yang memakainya tidak akan pernah mengetahui. Hingga kelak datang juru penengah, Tuhan, untuk memberikan putusan yang inkrah terkait keasliannya. Baik drama Nathan the Wise maupun teologi irja’ sama-sama menekankan pada penundaan vonis.
Kesimpulan saya, pembacaan komprehensif terhadap sejarah, interpretasi yang kreatif terhadap kitab suci, hingga mengkreasikan teologi adalah langkah menyemai toleransi. Hanya dengan demikian, toleransi mempunyai pijakannya yang kokoh dan tidak mudah goyah. Toleran tanpa pijakan tidak pernah benar-benar cukup. Karenanya, kita perlu toleran sekaligus kreatif, bukan?








Tinggalkan Balasan