Ratusan Juta untuk Selawatan, Salahkah?
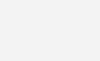
Salah seorang guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) membuat status pendek di laman Facebooknya. Ia menyinggung ihwal takbir keliling dan selawatan yang menghabiskan puluhan hingga ratusan juta. Ia bertanya-tanya apakah umat Islam di sekelilingnya sudah bisa sekolah, sudah bisa makan, sudah bisa berobat.
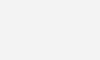
Bagi saya itu pertanyaan sekaligus sebuah larangan. Barangkali, ia bermaksud agar tidak membuat acara seremonial yang menghabiskan uang ratusan juta, padahal di saat yang sama banyak orang yang membutuhkan uang tersebut. Kesimpulan saya ini bisa keliru, namun saya ingin mengungkapkan bahwa fenomena selawatan—yang kerap menghabiskan biaya fantastis—memang meresahkan.
Tidak Salah, Kurang Patut Saja
Fenomena mengadakan selawatan yang menghabiskan uang ratusan tidak bisa kita anggap salah. Dengan catatan, uang untuk selawatan tersebut bukan kepunyaan orang lain. Seumpama organisasi kemasyarakatan, masjid, atau bahkan individu menggelar acara tersebut, maka tidak salah sepanjang uang sebanyak itu kepunyaan mereka. Kendati begitu, hidup tidak hanya soal benar dan salah.
Ada yang lebih penting daripada hitam-putih dan salah-benar, yakni kepatutan. Kita tidak bisa menyalahkan orang atau golongan yang merogoh saku celananya sedalam mungkin hanya untuk selawatan. Sebab, itu duit mereka dan hasil kerja keras mereka. Namun, kita bisa melihat dari kacamata pantas atau tidaknya hal tersebut, padahal di sekelilingnya banyak yang membutuhkan.
Dari tesmak kepantasan inilah, fenomena tersebut dapat kita sangkal. Memang, rasa-rasanya kurang bijak kalau menggelar acara selawatan ratusan juta namun sekelilingnya masih banyak yang lapar juga. Ini bukan berarti tidak suka selawat. Namun, selawat juga bisa kita laksanakan dengan sesederhana mungkin ‘kan?
Supply and Demand
Satu hal yang luput dari perhatian dari status Facebook guru besar di atas, yakni posisi pemuka agama. Pemuka agama yang saya maksud di sini bisa gus, kiai, habib bahkan. Di fenomena tersebut, para pemuka agama alih-alih memberikan pencerahan, malah menyediakan jasa layanan. Bukankah permintaan (demand) dari masyarakat kemudian terpenuhi oleh supply ini?
Dengan bahasa kasar, para pemuka agama di persoalan tersebut justru menjadi kreator. Merekalah juga bertanggungjawab atas tarif fantastis untuk selawatan. Andai saja, tarif yang mereka tetapkan juga tidak sedemikian besar, maka tidak akan ada persoalan ini. Meski begitu, mereka bukan aktor Tunggal atas terciptanya fenomena selawatan ratusan juta.
Antara orang yang meminta dan penyedia layanan selawatan, keduanya sama-sama kreator yang kompak. Coba bayangkan salah satunya saja tidak kompak, tentu tidak akan pernah ada fenomena ini. Misalnya, tidak ada yang meminta untuk selawatan dengan sebegitu meriahnya hingga menghabiskan banyak dana. Kalau tidak, coba bayangkan semisal para pemuka agama tidak memenuhi permintaan tersebut.
Dari fenomena ini kita belajar bahwa beragama tidak melulu soal benar dan salah. Ada kepantasan yang harus kita perhatikan juga. Demikian juga tidak melulu persoalan ritual atau ibadah semata, melainkan kesalehan sosial terhadap sesama manusia. Dua hal ini harus imbang karena sama pentingnya.







Tinggalkan Balasan