(Tidak) Ada Paksaan dalam Beragama
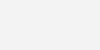
Salah seorang penulis Turki prolifik, Mustafa Akyol, menyajikan sebuah kisah menarik di dalam bukunya, Why, as a Muslim, I Defend Liberty? Hikayat ini berasal dari pengalaman personal Akyol tatkala bertolak dari konferensi di Arab Saudi. Di dalam pesawat, perempuan-perempuan Arab Saudi yang hendak menuju Turki menggunakan pakaian yang serba tertutup.
Semuanya berubah ketika pesawat perlahan mendekati Istanbul. Beberapa perempuan pergi ke lavatori, lantas keluar dengan pakaian yang lebih terbuka. Bahkan “salah seorang perempuan, saya bisa katakan, menggunakan rok paling mini yang pernah saya lihat” kata Akyol. Ia menduga bahwa perempuan-perempuan itu hendak mengunjungi salah satu kelab malam terkenal di Istanbul.
Akyol dengan tegas menyatakan bahwa kita tidak bisa menilai mereka sebagai orang hipokrit. Mereka tidak punya pilihan bebas di Arab Saudi untuk menggunakan pakaian yang terbuka. Kerjaan Arab Saudi yang konservatif memaksa mereka menggunakan sesuatu yang tak mereka inginkan.
Hemat saya, hal yang bisa kita teladani dari fragmen cerita tersebut ialah bahwa paksaan—apalagi dengan kekerasan—tidak pernah menghasilkan apa-apa. Seorang yang dipaksa untuk untuk melakukan sesuatu tidak akan pernah menikmati itu. Alih-alih menikmati, mereka akan mencari cara untuk keluar dari belenggu tersebut.
Wajah Keberagamaan Kita
Ketika membaca tulisan Akyol tersebut, di kepala saya langsung tergambar rias keberagamaan kita yang penuh paksaan. Seorang anak yang diancam akan dipukul oleh orang kalau menolak untuk ibadah. Seorang anak yang dincam akan disita teleponnya manakala tidak mengaji. Ini merupakan gambaran sederhana, namun dengan efek yang tidak bisa kita remehkan.
Hal yang sama juga terjadi tatkala siang hari di bulan siam, ketika sebagian orang menutup paksa warung makan. Padahal, menutup warung makan tidak lantas membuat orang lain berpuasa. Apalagi untuk berpuasa secara sukarela. Tidak akan. Sebaliknya, selalu ada celah untuk tetap tidak berpuasa.
Kalau mau realitas yang lebih konkret ialah ketika seorang kelompok memaksakan ajaran mereka terhadap kelompok yang lain. Seorang teman, misalnya, menggebu-gebu mengatakan kepada saya bahwa Yesus bukan Tuhan, melainkan Nabi. Ia juga memberikan alternatif bahwa seharusnya umat Kristiani menganggap Yesus hanya sebagai nabi. Sebuah pandangan, yang dalam hemat saya, bukan hanya tidak logis melainkan tak punya pijakan teologis.
Beragama dengan Logis
Mengapa saya katakan tidak logis dan tak punya pijakan teologis? Pertama, kita akui bersama bahwa iman tersebut merupakan wilayah yang teramat personal. Kita mungkin bisa berbusa-busa mengatakan bahwa Yesus hanyalah nabi. Umat Kristiani juga mungkin bisa berpura-pura mengangguk seolah mengiyakan. Namun, di kedalaman hati mereka tidak akan pernah menganggap Yesus sebagaimana teman saya tadi.
Kedua, tidak mempunyai pijakan teologis untuk memaksakan itu. Sebuah potongan ayat yang terkenal di dalam Al-Qur’an kiranya cukup untuk menerangkan ini. Bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Membahas ayat ini, saya jadi teringat buku Christine Schirrmacher Let there be no Compulsion in Religion (Sura 2:256). Sebuah buku yang mendiskusikan ihwal kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
Kembali pada soal paksaan bahwa tindakan secama itu—bagaimanapun bentuknya—mendapat tantangan serius dari kitab suci itu sendiri. Ada satu lagi potongan menarik dari surah Yunus:99 yang menyatakan bahwa jika Tuhan menghendaki semua orang di bumi ini tentu bakal seiman. Faktanya, diversitas keimanan di muka bumi adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah. Artinya? Tuhan tidak mau umatnya seragam!
Dengan demikian, seseorang yang mencoba menyeragamkan keimanan, sekejap mata jatuh ke liang ketidaklogisan. Tidak hanya tidak logis secara teologis, melainkan juga secara sosiologis. Sesederhana bahwa realitas sosial yang heterogen tidak bisa direduksi untuk menjadi homogen. Sebabnya, penting untuk beragama secara logis dari berbagai aspeknya.
Walaupun begitu, saya tidak mengelak bahwa akan tetap ada orang yang beragama dengan tidak logis. Sebagaimana juga akan tetap lestari orang-orang yang melakukan paksaan dalam beragama. Judul tulisan ini kiranya mampu mengurai hal tersebut secara presisi. (Tidak) Ada Paksaan dalam Beragama. Di detik yang sama menyiratkan bahwa ada paksaan dalam beragama.
Tidak ada paksaan secara teologis, namun secara empiris sehari-hari pasti ada. Tantangannya, apakah kita bisa memaksa orang-orang agar tidak memaksakan kehendak? Pertanyaan yang ambigu dan hanya bisa kita jawab di dalam hati. Titik ambigunya ialah ketika jawabannya afirmatif, berarti kita akan terjatuh pada pemaksaan yang sama.
Kiranya, jawaban paling ideal adalah dengan tidak menjawab. Membiarkan orang-orang yang suka memaksa itu dengan jalannya, tanpa kita paksa untuk berubah. Dengan keyakinan di hati bahwa tindakan mereka tidak mempunyai pijakan teologis—apalagi sosiologis. Sebab inilah bentuk selemah-lemahnya iman.




Tinggalkan Balasan