Antisipasi Ramadan sebagai Bulan Perpecahan
Contents
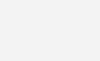
Rasa-rasanya tidak ada yang menyangkal perihal keagungan bulan Ramadan. Nyaris setiap aspek di bulan ini satu setrip di atas bulan lain. Dari aspek ibadah, terdapat ritual siam yang secara khusus hanya absah dilaksanakan di bulan ini.
Dari aspek lain, terdapat euforia dan ekspresi keberagamaan yang semakin meningkat. Sepanjang siang harus menahan haus dan lapar. Saat malam lanjut salat tarawih hingga tadarusan. Kurang ekspresif apalagi ibadah di bulan Ramadan ini?
Sayangnya, ada satu dimensi yang oleh kebanyakan orang tidak mendapat perhatian. Dalam hemat saya, bersamaan dengan spesialnya bulan Ramadan ini, juga ada potensi lain yang timbul daripadanya. Sebelumnya, kita harus menyepakati bahwa bulan ini bulan suci. Sebagaimana juga nanti harus sepakat bahwa ada kemungkinan negatif yang muncul di dalamnya. Kendati demikian, potensi semacam itu tidak bisa mematahkan keagungan Ramadan.
Sebab, potensi itu berada pada taraf yang spekulatif dan tidak niscaya. Berbeda dengan keagungan Ramadan yang memang tak terbantahkan. Potensi negatif yang saya maksud adalah kemungkinan Ramadan menjadi bulan perpecahan. Bulan di mana membuat umat Islam berseteru satu sama lain.
Ada tiga hal yang menguatkan pandangan saya ini dan masing-masing akan kita bahas lebih lanjut.
Penepatan Awal Ramadan
Pertama, penetapan awal bulan yang lazimnya penuh perbedaan. Semula hal tersebut adalah sah-sah belaka, karena memang ruang ijtihad. Dengan kata lain, perbedaan tersebut pemicunya adalah perbedaan kerangka epistemologis untuk menentukan awal bulan. Antara pengguna hisab dan pengguna ru’yat al-hilal. Tidak mujur, hal tersebut tak berhenti hanya pada ranah espitemologi, melainkan melangkah lebih jauh dan mengkristal menjadi ideologi.
Susiknan Azhari—salah seorang pakar falak—mengungkapkan transformasi dari perbedaan epistemologi ke ideologi menjadi akar sebuah konflik. Ia kemudian menyitir cerita Hamka yang menggambarkan relasi konfrontatif tersebut. Pernah terjadi di Belawan di mana hilal telah terlihat dan sudah lapor ke kadi kerajaan Deli. Naifnya, dicarikan dalil untuk menolak kesaksian tersebut, musabab kalau diterima akan sama lebarannya dengan pengguna hisab.
Cerita tersebut mengilustrasikan bahwa sentimen antara hisab-rukyat mengakar sedemikian kuat. Seterusnya, pengguna hisab bisa menginterupsi bagaimana bisa pengguna rukyat masih kolot dan tidak akomodatif terhadap sains modern.
Pada saat yang sama pihak rukyat bertahan dan memukul balik mereka dengan anggapan metode hisab menyimpang dari zahir Al-Qur’an dan hadis. Fenomena semacam ini jika tidak dimediasi dengan baik, maka akan berakibat fatal, perpecahan dan ketidakrukunan.
Penentuan Awal Syawal
Perbedaan tersebut membawa pada potensi perpecahan kedua. Kemungkinan perbedaan dalam menentukan akhir bulan puasa atau menentukan masuk tidaknya 1 Syawal. Dengan ungkapan yang berbeda yakni terkait dengan penentuan hari lebaran. Menarik, Suskinan Azhari (2020) mencatat pada lebaran tahun 2017 secara formal memang serempak pada 25 Juni. Namun, secara praktik terdapat empat hari lebaran yang terjadi pada saat itu. Intinya bahwa penentuan awal bulan Syawal masih menyisakan celah perbedaan.
Dengan begitu, umat muslim potensi terpecah belah sebelum memasuki Ramadan dan menjelang berakhirnya. Lalu, apakah di tengah-tengah tidak ada potensi perpecahan itu? Jangan salah. Sepanjang bulan Ramadan potensi itu ada, hanya saja kurang terekspos. Perbedaan jumlah rakaat tarawih antara dua ormas gigantis Indonesia yang potensial menjadi perpecahan kalau tidak kita dengan arif dan bijak.
NU dan Muhammadiyah
Nadlatul Ulama kokoh dengan jumlah rakaat tarawih sebanyak 20 plus 3 witir. Sementara, Muhammadiyah memilih jumlaah separuhnya. Hanya 8 salat tarawih lanjut 3 salat witir saja. Uniknya, secara praktis di dalam Muhammadiyah pun masih terjadi perbedaan formasi. Antara dua rakaat salam (2-2-2-2-3) dan empat rakaat salam (4-4-3). Namun, perbedaan dalam hal ini tidak potensial memantik perpecahan, musabab masih dalam satu barisan.
Keduanya tentu memiliki pijak normatif masing-masing. Baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah tidak akan beribadah tanpa patokan nas yang otoritatif. Sayangnya, beberapa orang yang saya temui menganggap bahwa tarawih ala Muhammadiyah tidak sahih. Pada saat yang sama menganggap praktik 20 rakaat yang paling sesuai syariat. Demikian juga sebaliknya kritik terhadap tarawih Nahdlatul Ulama.
Kritik semacam itu dapat diterima dan sah-sah saja sepanjang masih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, terdapat hal lain yang harus diperhatikan dengan lebih bijaksana. Kritikan semacam itu akan memantik gesekan yang kurang mengenakkan. Tidakkah cukup gesekan awal bulan dan akhir bulan Ramadan? Tidak bijaksana kalau nambah gesekan akibat perbedaan rakaat tarawih.
Akhirulkalam, sudah waktunya perdebatan semacam itu diakhiri—sebagai proteksi dampak yang lebih besar (perpecahan) di bulan suci ini.(**)











Tinggalkan Balasan