Sudah Saatnya Memimpikan Ormas yang Oposan
Contents
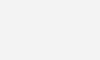
Sederet kejadian yang belakangan banyak dibicarakan khalayak memang membuat pening. Dipantik isu naiknya biaya kuliah, putusan Mahkamah Agung, hingga nasib kebebasan pers di tangan RUU Penyiaran. Merasa itu belum cukup, kemudian lahir konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Di waktu yang sama pula, Ijtima Ulama Nasional VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa. Sebuah fatwa yang mengharamkan salam lintas agama dan ucapan hari raya.
Pendek kata, batin masyarakat luas mendapat tekanan dari berbagai penjuru. Apalagi ketika jatah konsesi tambang diberikan kepada ormas sebesar Nadlatul Ulama (NU). Tanpa berpikir Panjang, ketua umum, Yahya Cholil Staquf, menghaturkan terimakasih dan apresis kepada Presiden Joko Widodo. Di seberangnya, Muhammadiyah tampil lebih bijak dengan mencoba untuk membahasnya terlebih dahulu. Meskipun ujung-ujungnya menerima dan menyetujui juga.
Di detik yang sama, fenomena tersebut dengan gamblang memperlihatkan relasi ormas dan negara. Dalam panggung sejarang, relasi keduanya memang penuh dinamika. Penting dicatat sejak dini bahwa MUI tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ormas seperti NU. Hanya untuk kepentingan analisis kita dapat memasukkan dalam lingkaran itu. Secara ringkas, hubungan antara negara, NU dan MUI mirip cinta segitiga. Saling tarik menarik antara yang satu dengan lainnya.
Orde Baru vis a vis Ormas Keagamaan
Presiden Soeharto mempunyai peran sentral atas berdirinya MUI. Sebagai kalkulasi politis, ia merasa perlu mendapat suplai suara umat Islam. Sikap yang tidak begitu dominan sebelum-sebelumnya. Sepanjang masa pemerintahan Orde Baru, posisi MUI tidak begitu nampak menjadi oposisi negara. Agaknya cukup beralasan manakala sebagian kalangan menilai lembaga ini sebagai anak rezim. Rentang yang cukup lama, MUI berada di zona nyaman hingga Soeharto lengser dari tampuk kepemimpinan.
Jatuhnya Orde Baru tidak otomatis membuat MUI jauh dari lingkaran kekuasaan. Buktinya, ketika Habibie naik dan mendapat banyak kritikan, MUI menjadi defender yang kokoh. Kendati bukan fatwa yang MUIj keluarkan, melainkan tausiah, tetapi menunjukkan kecenderungan lembaga fatwa ini. Barangkali hal tersebut berkelindan erat dengan figur Habibie yang mereka nilai sebagai muslim yang ideal. Posisi ini nyaris sepenuhnya berbeda ketika pemerintahan berikutnya, Abdurrahman Wahid.
Gus Dur vs MUI
Saya kira, salah satu hal yang menjadi penyebab ialah sosok Gus Dur sendiri. Seorang intelektual yang sikap kritisnya tidak tebang pilih. Fatwa-fatwa yang terbitan MUI, tidak jarang mendapat counterattack dari Gus Dur. Mulai dari fatwa soal Ajinomoto hingga keharamaan ikut perayaan Natal. Terkait yang terakhir ini, kita bisa melihat sikap Gus Dur di tulisannya yang bertajuk Fatwa Natal, Ujung dan Pangkal. Sebabnya, tak berlebihan kalau kita katakan bahwa Gus Dur kritikus MUI nomor wahid.
Berbeda dengan MUI, posisi NU yang sejak lama menjadi rumah bagi Gus Dur lebih bersifat kooperatif. Wajah oposisional NU terhadap negara yang paling nampak hanya pada era Orde Baru. Lain dengan Soeharto, NU lebih dekat dengan presiden sebelumnya. Ini berarti bahwa NU di masa Orde Baru cenderung berhadapan dengan negara—kalau tidak membuang muka.
Jejak tersebut menyajikan ilustrasi bahwa antara negara, NU dan MUI saling tarik ulur. Meski tidak sepenuhnya, tatkala NU bergandeng mesra dengan kekuasaan, MUI relatif menjaga jarak, demikian sebaliknya. Gambaran ini juga nampak pada dua periode Presiden Joko Widodo. Bagaimana kedekatan satu ormas dengan negara seolah menjadikan satunya menjauh. Atas dasar ini, tidak naif untuk memimpikan ormas Islam menjadi oposisi, di samping partai politik.
Ormas Keagamaan yang Oposan
Salah satu maujud esensial di negara demokrasi ialah keberadaan oposisi. Ini juga merupakan topik yang tidak bisa dilewatkan ketika membincang lanskap Indonesia pascapilpres. Sebabnya, beberapa partai yang kalah dengan sadar penuh bergabung ke barisan pemenang. Walau tidak keseluruhan, hal itu menyajikan lanskap negara yang tidak baik. Itu melanggar aturan main bahwa tidak akan pernah terwujud pemerintahan yang sehat tanpa oposisi. Bukan sembarang oposisi, melainkan oposisi dengan kekuatan yang sepadan, tak kalah gemuk dibanding koalisi.
Tepat di titik inilah, ketika banyak partai tidak bisa menjadi harapan, satu-satunya kemungkinan adalah ormas Islam. Sebagaimana ilustrasi di atas bahwa relasi ormas dengan negara nampak fleksibel. Artinya, bukan hal yang muhal memimpikan ormas Islam menjadi oposisi. Dalam hal ini, bisa menengok ke belakang ke jejak-jejak Front Pembela Islam (FPI) sebelum bubar barisan. Meskipun harus kita sadari bahwa kemungkinan NU menjadi oposisi sangat kecil, beruntung tidak tertutup. Keberpihakan ormas ini di tiga pemilu terakhir lebih dekat dengan petahana.
Ini berarti bahwa semata-mata MUI yang mempunyai potensi besar menjadi oposisi selama beberapa tahun mendatang. Barangkali di belakangnya juga berdiri kokoh Muhammadiyah. Naluri oposan MUI ini nampak ketika kerap berbeda dengan negara, utamanya mengenai urusan keagamaan. Perbedaan pandangan antara MUI dan Kementerian Agama ihwal salam lintas agama dapat kita baca dalam logika koalisi-oposisi. Naluri tersebut akan lebih terasa manakala kritik (baca: fatwa) MUI lebih ekstensif sekaligus distingtif dengan pemerintah.
Hanya dengan begini, oposisi yang selama ini kita impikan akan terwujud di tangan ormas keagamaan (MUI). Harus kita akui bersama bahwa tidak cukup hanya dengan satu satu dua partai yang menjadi oposan. Perlu kekuatan yang lebih besar lagi agar oposisi yang ideal dapat terwujud. Kekurangannya terletak pada anatomi MUI sendiri yang tidak sepenuhnya lepas dari negara. Meminjam istilah Moch. Nur Ichwan (2024) ia adalah lembaga semiresmi. Dengan kata lain, ada titik-titik di mana MUI juga bakal bergandeng mesra.
Menilik Masa Depan
Konklusi dari hal ini ialah probabilitas ormas Islam untuk menjadi oposisi hanya mungkin di tangan MUI. Sukar mengharap wajah oposisional NU tatkala menilik dari hubungannya yang mutakhir dengan pemerintah. Semestinya, ormas keagamaan kita menjadi pemain terakhir. Ketika semua kalangan sudah tidak nyaman menjadi oposisi, ormas keagamaan mesti mengisi ruang kosong itu.
Tidak berlebihan dan memimpikan ormas yang tidak mudah mengangguk kepada pemerintah. Pertanyaannya, sejauh mana ormas dapat bertahan menjadi oposisi yang memang tidak pernah nyaman? Wallahualam.





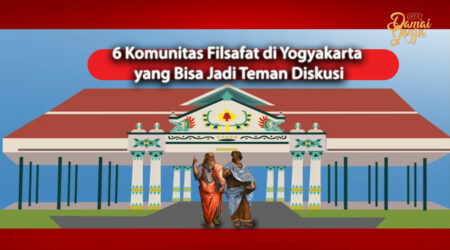



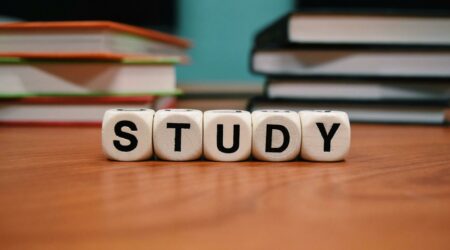


Tinggalkan Balasan