Pendidikan Hanya Kebutuhan Tersier, Benarkah?
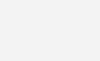
Apa benar dunia pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja? Minggu lalu, tepat sejam sebelum saya wisuda, seorang teman membuat story di media sosial. Saya ingat betul kata-katanya bahwa ia akan membuktikan untuk sukses tidak butuh titel sarjana. Mengingat ia hanya teman di media sosial dan tak akrab, saya anggap itu hanyalah sebuah kebetulan. Maksudnya bukan lagi menyindir saya yang hendak prosesi wisuda.
Hal itu pula yang membuat saya berpikir bahwa jangan-jangan arti sukses versi dia itu berbeda. Bagi saya dan orang-orang kampus, misalnya, sukses itu ketika kita berhasil menyandang predikat sarjana. Syukur-syukur kalau suatu saat bisa menjadi seorang guru besar. Pertanyaannya, apakah bagi orang di luar sana itu merupakan kesuksesan? Jawaban saya sampai taraf ragu—menghindari kata tidak.
Karenanya, alih-alih geram ketika mendengar Tjitjik Thajandarie mengatakan bahwa pendidikan adalah kebutuhan tersier, saya memilih merenung sejenak. Jangan-jangan ungkapan pejabat di Kemendikbud ini memang benar. Bahwa pendidikan bukan kebutuhan yang amat mendesak sehingga ia hanya sampingan belaka. Umpama dibandingkan makan siang gratis jelas kalah, karena ini merupakan kebutuhan primer.
Namun, untuk menjawab tersebut secara pas, maka perlu berpikir tujuan pokok dari sekolah dan pendidikan. Kalau jawabannya semata-mata mendapat pekerjaan yang layak, kita akan tertampar keras oleh fakta. Tidak sedikit sarjana yang menganggur, termasuk saya. Kalau tidak begitu, bekerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang kita tekuni selama kuliah. Ingat kata Mas Nadiem bahwa 80 persen sarjana itu kerja tidak sesuai bidang.
Menghadapi Persoalaan dengan Realistis
Saya mulai bersikap realistis melihat persoalan ini, apalagi biaya kuliah sedang naik-naiknya. Mari kita kalkulasi saja semisal kuliah S1 4 tahun menghabiskan duit ratusan juta. Hanya orang-orang tertentu yang bisa balik modal sebentar pascalulus. Artinya, kebanyakan orang kuliah tidak balik modal, kalau tidak tekor. Padahal, selain air dan udara, duit merupakan sumber kehidupan.
Mari kita bayangkan bagaimana kalau setelah lulus memilih untuk menikah. Padahal, dengan titel sarjana yang kita punyai belum mampu menghasilkan apa-apa. Akibatnya, rela bekerja apa saja asal istri dan anak di rumah tidak kelaparan. Kalau dua juta orang Indonesia punya pandangan seperti ini, bukankah angka sarjana yang bekerja tidak sesuai kualifikasi akan semakin membangkak?
Kalau memang demikian kenyataannya, berarti ilmu yang sewaktu kuliah tidak berguna. Sehingga, terasa cuma-cuma menghabiskan duit puluhan hingga ratusan juta kalau akhirnya tidak terpakai. Sebab itu, ada benarnya kata Tjitjik kalau pendidikan ini hanya kebutuhan tersier saja. Bukan sesuatu yang mendesak, sebagaimana makan dan minum (tentu ini tambahan dari saya pribadi).
Sekali Lagi, Pendidikan juga Realistis
Anda boleh mengira bahwa pandangan saya ini sangat naif, kalau tidak bodoh. Bagaimana mungkin seorang sarjana (predikat cumlaude pula) menyetujui bahwa pendidikan hanya kebutuhan tersier. Apabila praduga ini muncul di benak Anda, maka jawaban saya hanya satu: realistis saja. Daripada menghabur-hamburkan duit buat bayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) kenapa tidak berwirausaha saja? Toh ujung-ujungnya ilmu yang dipelajari tidak terpakai.
Hari ini, bagi kebanyakan orang sukses itu bukan lagi kuliah di mana, bergelar apa, atau bahkan publikasi Scopusnya berapa. Di kampung saya, kesukseskan itu terkait kerja apa, penghasilannya berapa, hingga mobilnya apa. Karena itu, mari tidak usah marah-mara kepada Tjitjik yang meletakkan pendidikan bukan kebutuhan primer. Sebaliknya, sebagai kaum terpelajar, alangkah baiknya kalau direnungkan secara berjamaah apa yang salah dari pendidikan kita. Orientasi kah atau UKT yang tidak ramah kantong kalangan bawah?

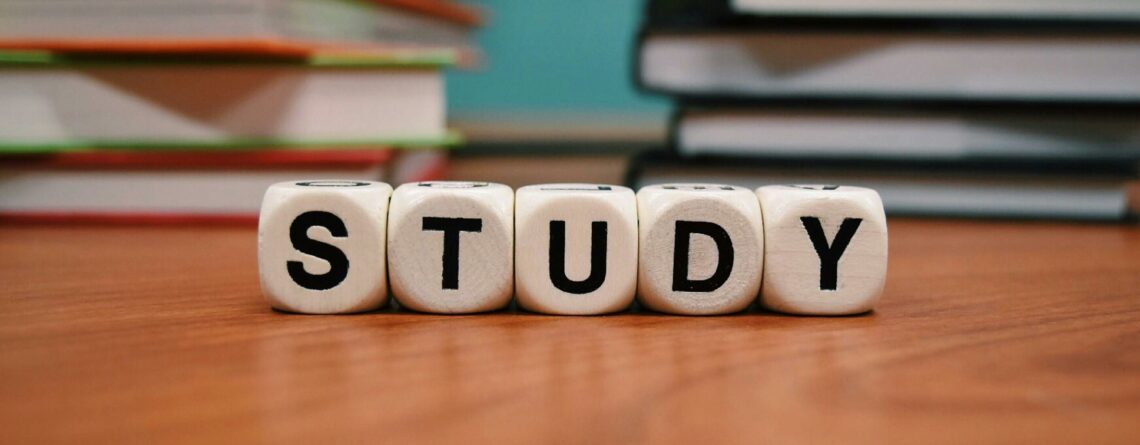



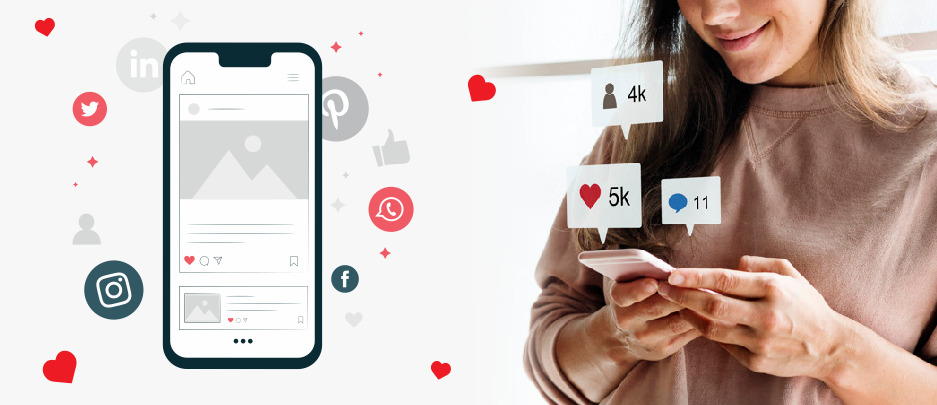





Comment (1)
[…] saja telah selesai. Sudah pula di ACC dosen pembimbing. Tapi tidak sampai tahap ini saja. Para mahasiswa harus berhadapan dengan dewan penguji yang seringnya jauh dari ekspektasi. Teman-teman kadang […]