Mubeng Beteng, Bukti Kebersamaan Rakyat
“Saat simbah kakung masih hidup, malam satu suro menjadi malam yang ditunggu-tunggu. Biasanya simbah akan puasa pati geni (puasa tidak berbicara) sebelum malamnya menjalani ritual ngumbah gaman (mencuci pusaka)”
Orang Jawa menyambut Suro dan Muharram dengan berbagai perayaan dan pensakralan. Hal ini tidak terlepas dari penanggalan Jawa dan kalender Hijriah yang memiliki korelasi dekat. Menurut Muhammad Sholikhin dalam bukunya Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa; pengaruh kontrol kraton yang kuat melatarbelakangi tindakan revolusioner Sultan Agung dalam upayanya mengubah sistem kalender Saka (perpaduan kalender Jawa asli dengan Hindu) menjadi penanggalan Jawa yang merupakan perpaduan kalender Saka dan kalender Hijriah.
Revolusioner ini membuat bulan Suro atau Muharram dianggap istimewa.
Berbagai tempat mengadakan perayaan untuk memperingatinya, bukan sekedar untuk kegiatan keagamaan namun perayaan kultur budaya dengan mengangkat berbagai tradisi masyarakat.
Di Kota Yogyakarta, Suro atau Muharram dirayakan dengan prosesi Lampah Budaya Mubeng Beteng. Seperti namanya, Lampah Budaya Mubeng Beteng adalah ritual berjalan kaki mengelilingi benteng yang memagari keseluruhan wilayah Kraton Yogyakarta.

Tradisi tersebut sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram di Kotagede ratusan tahun silam yang dilakukan oleh Prajurit Kraton untuk menjaga keamanan wilayah Kraton. Dalam tradisi ada pantangan yang harus ditaati oleh yaitu tidak boleh bersuara apalagi berbicara dengan yang lainnya. Pantangan berbicara inilah yang sering dikatakan sebagai Topo Bisu alias tidak berbicara. Selain itu dilarang makan dan minum selama prosesi.
Walau melelahkan, tentu saja kegiatan ini bukan tanpa makna. Lampah Budaya Mubeng Beteng bertujuan untuk bersyukur, mendoakan keselamatan lahir dan batin bagi bangsa, negara, keluarga, hingga diri sendiri. Melakukan instropeksi diri atas perbuatan yang telah dilakukan selama setahun terakhir, serta berjanji untuk memperbaiki di tahun-tahun mendatang untuk menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari.
Prosesi berjalan dilakukan dengan rute ke arah barat kemudian ke selatan, ke timur, baru ke utara, dan kembali ke tempat dimulainya prosesi ini. Dimulai dari Ndalem Ponconiti, kemudian berjalan melalui jalan Rotowijayan, jalan Agus Salim, jalan KH Wahid Hasyim, pojok Beteng Kulon, Plengkung Gading, pojok Beteng Wetan, jalan Brigjen Katamso, jalan Ibu Ruswo, Alun-alun Utara, dan baru kembali ke Ndalem Ponconiti. Totalnya sekitar empat kilometer atau dibutuhkan waktu sekitar satu setengah jam untuk menyelesaikannya.
Lampah Budaya Mubeng Beteng menjadi bukti kebersamaan rakyat yang terjalin di Yogyakarta. Melalui prosesi ini kita diingatkan meskipun diam, sebenarnya rakyat bukan pasif tapi juga tetap bersuara. Adanya hoax, ujaran kebencian, dan teror merupakan ancaman bagi persatuan bangsa. Melalui filosofi Lampah Budaya Mubeng Beteng, semoga kita dapat merevitalisasi kembali semangat gotong-royong bersama melawan hal-hal yang memecah kesatuan Negara Indonesia dengan membentenginya dari Kota Yogyakarta.
Ditulis oleh : @catherine.cece


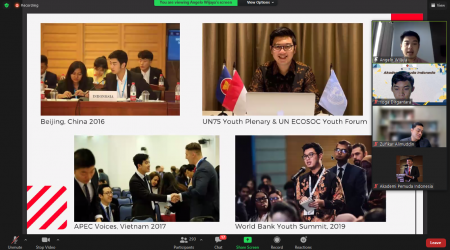






Tinggalkan Balasan