Cultural Reinforcement Sebagai Antiseptik Mimbar Radikal
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beberapa waktu lalu merilis beberapa ciri penceramah radikal. Direktur Utama Pencegahan Badan nasional Penanggulangan Terorisme, Brigjen. Akhmad Nur Wakhid menguraikan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam rapat pimpinan TNI/Polri Selasa (1/3), menyampaikan peringatan untuk tidak mengundang penceramah radikal. Himabauan ini menjadi alarm bagi kita agar tidak semabarangan mengundang atau menghadirkan penceramah dalam mimbar agama.
Halaqah, safari dakwah, dan pengajian sering kali menjadi sarana doktrinasi bagi oknum penceramah radikal dengan dalil-dalil intoleransinya. Masyarakat digiring untuk membenci yang berbeda serta anti ideologi berbangsa dan bernegara. Mereka yang tak mempunyai pondasi kuat ilmu agama akan mudah terprovokasi dan terpecah belah, bahkan parahnya mereka dapat melakukan tindak fisik yang mengarah pada kasi terorisme.
Oleh karena itu, penting kiranya kita melihat latar belakang dan sanad setiap penceramah baik dalam bidang keilmuan maupun likungannya. Peran aktif masyarakat sebagai garda terdepan melawan radikalisme harus dimasifkan. Keanekaragaman di negeri ini memang sering dijadikan modal penting meramu radikalisme. Lantas bagaimanakah kita menyikapi keniscayaan ini?
Moderasi agaknya menjadi problem solving paling signifikan di era ini, tetapi untuk menuju konsep tersebut maka perlu alat atau narasi sebagai kendaraan agar tercapai konsep moderat. Penguatan budaya meruapakan salah satu cara mendorong masyarakat untuk terus membina kasalehan sosial. Ditinjau dari perilaku keagamaan masyarakat Indonesia terbagi pada tiga golongan yaitu kaum abangan, kaum santri, dan kaum priyayi. Harmonisasi antar ketiga episentrum ini menjadi kunci penting merawat perdamaian.
BACA JUGA: Urgensi Vital Pemberdayaan & Pengabdian Masyarakat
Dahulu para pendakwah atau ulama menyebarkan agama islam melalui akulturasi budaya. Para muballigh tersebut menggunakan budaya tradisional masyarakat Indonesia sebagai alat untuk masuk dalam dimensi-dimensi spiritual. Wali Songo merupakan salah satu contoh bagaimana penerapan akulturasi budaya tersebut. Wayang, tradisi ambengan, ruwahan, ingkungan, sedekah desa dan masih banyak lagi bentuknya. Konsep dakwah Wali Songo menempatkan budaya sebagai unsur utama yang dapat diselaraskan dengan ajaran agama, sehingga Islam tidak memudarkan budaya masyarakat.
Cliforts Geertz berpendapat bahwa budaya adalah sistem simbolik yang kompleks, di mana makna-makna sosial dikonstruksi melalui tindakan-tindakan sosial dan simbol-simbol yang digunakan oleh individu dalam suatu masyarakat. Ia menekankan bahwa untuk memahami budaya, kita perlu memperhatikan konteks lokal, praktik sosial, dan simbol-simbol yang digunakan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Anggapan Geertz ini menguatkan bahwasanya budaya bukanlah tembok penghalang penyebaran agama. Agama dan budaya adalah dua unsur yang saling melengkapi, apabila dua hal diramu maka eksistensi keduanya akan semakin kuat.
Pada dasarnya ritual-ritual keagaman lahir atas kontruksi budaya atau adat masyarakat. Sejarah lahirnya agama-agama di dunia tidak akan terlepas dari kondisi masyarakat pada waktu itu. Pemahaman masyarakat mengenai dogma-dogma dipengaruhi oleh adat yang berkembang disaat turunnya sebuah wahyu. Oleh sebab itu, pemahaman dan pengaplikasian religious experience disetiap wilayah berbeda-beda, batasannya adalah selama tidak keluar dari subtansi atau kaidah ajaran, maka sah-sahnya seorang umat mengekspresikan agama dengan versinya. Pemahaman inilah yang kemudian harus diluruskan agar tidak mudah menjust salah atau benar suatu narasi keagamaan.
Editor: Bennartho Denys



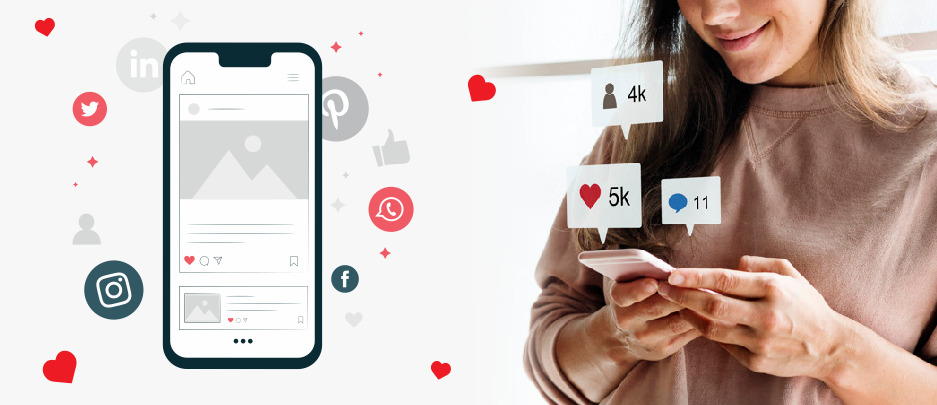







Comments (2)
[…] BACA JUGA: Cultural Reinforcement Sebagai Antiseptik Mimbar Radikal […]
[…] Peran Pendidikan dalam Deradikalisasi […]